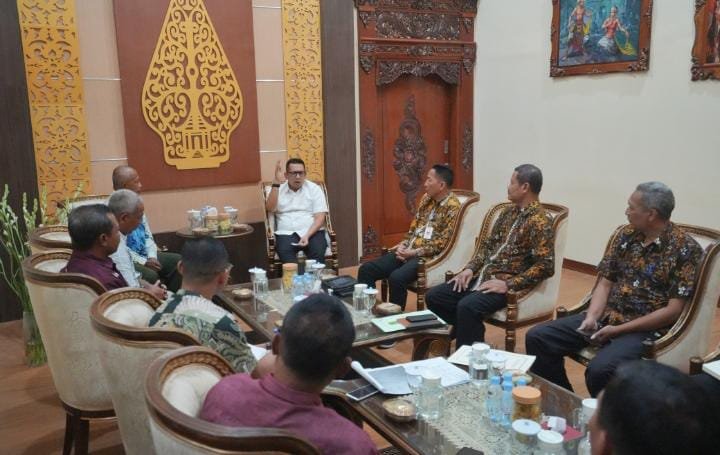Bangkalan, Media Pojok Nasional – Di balik rutinitas belajar-mengajar di berbagai sekolah dasar negeri, tersimpan persoalan laten yang jarang terangkat ke permukaan: status kepemilikan tanah sekolah yang belum jelas dan belum tersertifikasi. Masalah yang terlihat sederhana ini ternyata berbuntut panjang menyentuh aspek regulasi, budaya lokal, hingga rasa “takut melangkah” dari para kepala sekolah yang sejatinya hanya ingin memastikan proses belajar tetap berjalan.
Dalam penelusuran Media, seorang kepala sekolah yang ditemui sebut saja S, membeberkan bagaimana selama bertahun-tahun dirinya dihadapkan pada desakan untuk mengajukan sertifikasi lahan sekolah. Namun langkah itu tidak semudah yang dibayangkan.
“Ketika dimintai atasan untuk mengajukan sertifikasi, kami ini sebenarnya tidak berani melangkah. Ada masalah di bawah yang tidak tampak, dan itu yang membuat kami berhenti di tengah jalan,” ungkapnya.
Dari peristiwa itu S menggambarkan bahwa dirinya bukan tidak mau menjalankan instruksi. Namun kondisi lapangan menunjukkan ada persoalan mendasar pada status tanah yang ditempati sekolahnya mulai dari kepemilikan pribadi warga hingga batas lahan yang tidak pernah tuntas dibahas sejak sekolah itu berdiri.
Karena belum sah menjadi aset pemerintah, banyak sekolah kesulitan mendapatkan anggaran infrastruktur. Kerusakan bangunan, ancaman ambruk, hingga kebutuhan ruang baru sering mandek hanya karena status tanah tidak jelas.
S menggambarkan bahwa problem utama bukan hanya administrasi, tapi juga budaya lokal. Di beberapa desa, tanah yang dipinjamkan secara lisan atau “diikhlaskan dulu” oleh warga menjadi area sensitif ketika hendak disertifikasi. Ada rasa sungkan, ada kekhawatiran terjadi konflik, dan ada kecenderungan untuk tidak memperkarakan apa yang sudah dianggap “baik-baik saja”.
“Tidak semua yang tampak di permukaan itu menggambarkan kenyataan. Kadang orang yang kelihatannya protes belum tentu benar-benar ingin memprotes. Ini menyangkut budaya lokal, jadi kami memilih berpikir positif saja,” ujarnya.
Kini S mengaku sebagai pendidik ia memilih tidak memicu konflik dengan warga. Selama proses belajar berjalan, ia memilih bertahan pada situasi apa adanya.
Yang paling mengkhawatirkan, di berbagai daerah pernah terjadi sekolah tiba-tiba diminta mengosongkan lahan oleh pemilik. S membenarkan hal itu menjadi ketakutan tersendiri bagi mereka.
“Kami selalu memikirkan, kalau suatu hari pemilik lahan meminta sekolah dikosongkan, bagaimana dengan anak-anak? Proses belajar tidak boleh berhenti. Itu yang selalu kami antisipasi,” jelasnya.
Ia mengaku sudah menyiapkan kemungkinan-kemungkinan terburuk, berkoordinasi dengan komite, hingga membawa masalah ini kepada pengawas. Namun solusi permanen tetap bergantung pada status lahan yang tak kunjung tersertifikasi.
Meski menghadapi tekanan regulasi dan lapangan, S menegaskan bahwa hubungannya dengan masyarakat baik-baik saja. Tidak ada intimidasi atau konflik terbuka. Namun ia sadar, kondisi “damai di permukaan” tidak boleh mengaburkan masalah inti.
“Saya pastikan guru-guru dan siswa tidak pernah mendapatkan intimidasi. Tapi kalau lahan ini bermasalah, pemerintah harus menjamin proses belajar tidak boleh berhenti,” tegasnya.
Dari pengamatan investigatif ini, tampak jelas ada tiga simpul permasalahan:
- Status lahan sekolah yang tidak jelas selama puluhan tahun.
- Kebijakan sertifikasi yang tidak mudah dijalankan karena faktor sosial-budaya.
- Konsekuensi serius terhadap layanan pendidikan jika sengketa pecah.
Program sertifikasi nasional seperti PTSL sebenarnya menyediakan wadah penyelesaian. Namun tanpa keberanian dinas dan perangkat desa mengurai akar masalah di lapangan, proses ini akan terus tersendat.
(Anam)